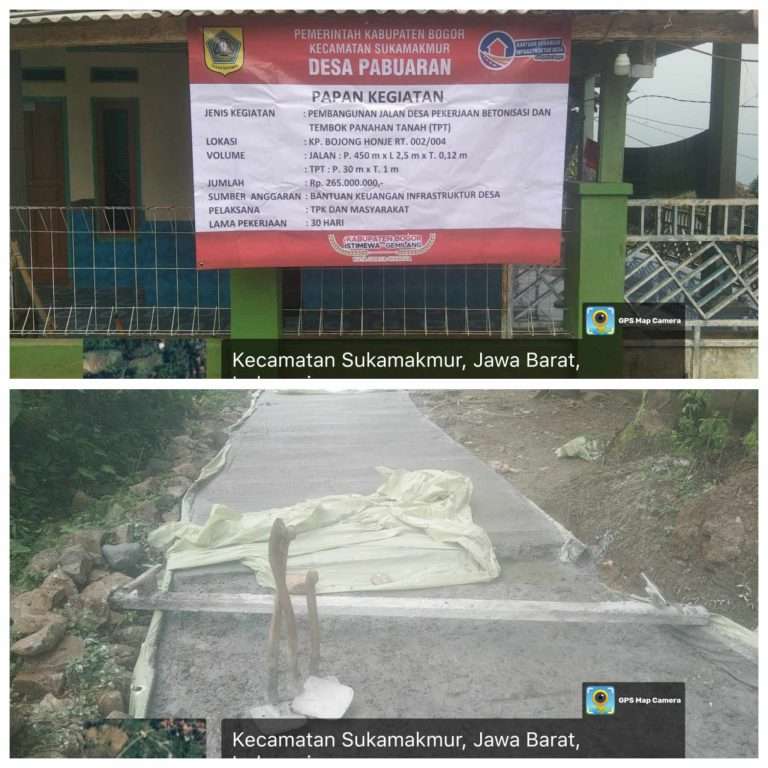MetronusaNews.co.id | Jakarta – Ketika jargon Presisi Polri digembar-gemborkan sebagai wajah baru Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, kenyataan di lapangan seringkali justru bertolak belakang. Pengalaman Wilson Lalengke dalam memenuhi undangan klarifikasi terkait AKBP Yunus Saputra, Kapolres Pringsewu Lampung yang dilaporkannya di Divpropam Polri menjadi salah satu contoh nyata betapa sulitnya menempatkan kepercayaan pada institusi yang justru kerap menunjukkan arogansi dan ketidakkonsistenan dalam menjalankan tugasnya.
Proses klarifikasi yang seharusnya menjadi ajang pencarian kebenaran, justru diwarnai oleh tindakan yang sangat mencederai asas transparansi. Larangan kepada Wilson Lalengke dan tim hukumnya untuk mengambil dokumentasi selama proses berlangsung adalah bentuk nyata dari praktik standar ganda yang tidak dapat dibenarkan. Sementara aparat Polri dengan bebas mendokumentasikan setiap langkah, pelapor justru diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak untuk melindungi dirinya dengan bukti pendukung.
Dalih “SOP internal Polri” yang dijadikan alasan pelarangan justru menunjukkan bahwa aturan internal tersebut berpotensi menjadi alat untuk menyembunyikan tindakan yang tidak profesional. Tindakan ini tidak hanya melanggar asas keterbukaan, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Lebih jauh lagi, larangan ini juga melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman pidana hingga dua tahun penjara.
Sikap penyidik yang melarang dokumentasi, bahkan meminta pengumpulan ponsel, mencerminkan arogansi aparat yang lupa bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Wilson Lalengke dengan tepat mempertanyakan: bagaimana mungkin aparat meminta bukti dokumentasi kepada pelapor saat laporan dibuat, namun melarang pelapor mendokumentasikan peristiwa yang dialaminya? Di mana logika dan keadilan dalam sikap seperti ini?
Kondisi ini semakin menguatkan kesan bahwa pelarangan tersebut adalah upaya untuk menciptakan ketertutupan. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa transparansi dalam proses klarifikasi menjadi sesuatu yang dihindari? Aparat Polri yang melakukan tindakan ini layak disebut sebagai “wereng coklat”, istilah yang dengan tajam menggambarkan mereka yang menggerogoti institusi dari dalam dengan perilaku buruknya.
Langkah Wilson Lalengke dan tim hukumnya untuk meninggalkan ruangan klarifikasi adalah bentuk perlawanan terhadap arogansi dan ketidakprofesionalan. Keputusan ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa tidak ada kompromi terhadap perilaku aparat yang melanggar prinsip transparansi dan keadilan. Dalam konteks ini, walk-out bukan sekadar tindakan emosional, tetapi sebuah pesan tegas bahwa rakyat tidak akan tinggal diam menghadapi penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang semestinya melayani masyarakat.
Ironi terbesar dalam kisah ini adalah laporan terhadap polisi oleh polisi, yang kemudian berujung pada laporan lain terhadap polisi yang menangani laporan tersebut. Ini adalah gambaran nyata dari kompleksitas dan kekacauan sistem hukum di Indonesia, di mana pelapor yang seharusnya mendapat perlindungan justru harus melawan lapisan demi lapisan birokrasi yang mempersulit perjuangannya.
Kejadian ini mencerminkan bahwa institusi Polri masih memiliki masalah serius dalam hal transparansi, profesionalisme, dan integritas. Slogan “Presisi” menjadi tidak lebih dari sekadar kata-kata kosong ketika aparat di lapangan justru menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai tersebut.
Kasus ini memberikan pelajaran penting, baik bagi institusi Polri maupun masyarakat. Bagi Polri, ini adalah peringatan bahwa reformasi internal bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Jika Polri ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, mereka harus berani membuka diri terhadap kritik, menghapus praktik-praktik yang merugikan keadilan, dan memastikan bahwa semua anggotanya memahami tugas sebagai pelayan masyarakat.
Bagi masyarakat, kasus ini mengingatkan kita bahwa keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan keberanian untuk melawan ketidakadilan, seperti yang ditunjukkan oleh Wilson Lalengke. Karena pada akhirnya, negara ini adalah milik rakyat, dan rakyatlah yang memiliki hak untuk menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dari mereka yang diberi wewenang untuk melayani.
Jika Polri ingin benar-benar menjadi lembaga yang Presisi, mereka harus membuktikannya dengan tindakan nyata, bukan hanya sekadar slogan. Dan ketika arogansi dan ketidakadilan terus berulang, rakyat akan tetap ada untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari suara kebenaran. (Tim)